Bersisa Mara di Baju Hijau

Menyoal Militerisme Sipil, Siklus Tak Berujung
****
Setelah menghilang lebih dari 20 tahun lalu, Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) berencana aktif kembali. Wacana itu mulai hangat sepekan terakhir sejak Komjen Listyo Sigit Prabowo, yang kini telah menjabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia memaparkan rencana agenda kerjanya di Senayan.
Listyo saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 20 Januari 2021 lalu berujar, Pam Swakarsa akan kembali aktif untuk menunjang ketertiban di tengah masyarakat. Keberadaan mereka bakal diintegrasikan dengan teknologi informasi dan berbagai fasilitas milik Polri.
“Sehingga Pamswakarsa bisa tersambung dengan petugas-petugas kepolisian," sahutnya kala itu, mengutip Tempo.
Jika sedikit mundur ke belakang, Listyo sebenarnya tampak sekadar menyahuti Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 yang ditandatangani Kapolri sebelumnya, Jenderal Idham Azis. Aturan ini menjadi legalitas keberadaan Pam Swakarsa. Namun yang dikedepankan adalah peran semacam petugas satuan pengaman (Satpam) dan satuan keamanan lingkungan di lingkup masyarakat.
BACA JUGA: EDITORIAL: Leaders are Readers
Dengan pembentukannya, negara berencana merekrut masyarakat sipil di lingkungan permukiman hingga perkantoran. Dalihnya untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban masyarakat, khususnya di masa pandemi.
Idham saat menandatangani Perkap itu pada 4 Agustus 2020 silam menuturkan, pengamanan dalam aturan baru itu berarti pengembang fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan masyarakat sendiri.
“Yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri,” ujar Idham.
Tak hanya Satpam atau pun Satkamling, pengamanan swakarsa juga dapat berasal dari kearifan lokal atau pranata sosial. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Rusdi Hartono mencontohkan peran pecalang di Bali sebagai wujud dari pengamanan dan ketertiban yang dimaksud.
“Bisa juga kita lihat contohnya itu siswa dan mahasiswa Bhayangkara,” kata dia, Selasa (26/1/2020) lalu.
Jejak Berdarah 1998
Riwayat Pam Swakarsa dapat dengan mudah kita telusuri sejak era reformasi silam. Harian Kompas pada November 1998 pernah mengungkap kerja pasukan swasta ini.
Jenderal Wiranto, yang kala itu menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengatakan, Pam Swakarsa berfungsi mengamankan Sidang Istimewa (SI) MPR, pada10-13 November 1998.
“Butuh mereka untuk mengamankan sidang istimewa MPR dari pihak-pihak yang akan menggagalkannya,” kata Wiranto.
Pihak yang dimaksud Wiranto adalah massa aksi dari kalangan mahasiswa. Ketika itu, sidang istimewa menuai protes. Massa menyesalkan tidak adanya perubahan anggota MPR dan Dwifungsi ABRI masih berjalan.
“Semua anggota di sidang tersebut masih dari rezim Orde Baru,” bunyi aspirasi mahasiswa, mengutip laporan Mengenal Pam Swakarsa, dari Tragedi Semanggi 1998 hingga Digagas Ulang Kapolri Baru di Pikiran Rakyat, 23 Januari lalu.
Namun situasi di lapangan berbeda. Pengamanan sidang istimewa itu justru berubah jadi bentrokan berdarah. Pam Swakarsa terlibat rusuh dengan massa aksi. Maria Katarina Sumarsih, ibu mendiang BR Norma Irmawan yang menjadi korban Tragedi Semanggi I pada 13 November 1998 silam, berkomentar tak lama usai wacana itu muncul di media massa.
Melalui akun Twitter-nya, Sumarsih mengenang, pemerintah saat itu tak hanya mengerahkan TNI/Polri untuk memukul mundur massa aksi, namun juga mengerahkan Pam Swakarsa.
"Mereka dipersenjatai bambu runcing untuk menghadapi mahasiswa yang berdemonstrasi untuk mengawal pelaksanaan reformasi," tulis Sumarsih, Jumat (22/1/2021).
Pam Swakarsa terlibat dalam pengerahan massa saat Tragedi Semanggi. Polda Metro Jaya kala itu menyebut, selain beberapa ormas Islam, kelompok lain juga terlibat dalam pasukan itu, termasuk Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, FKPPI, dan Warga Wijaya Indonesia.
Namun dugaan keterlibatan ormas Islam juga sempat diperdebatkan. Pasalnya dalam sejumlah penelusuran, diketahui banyak dari anggota Pam Swakarsa yang mengaku dibayar dan dibekali atribut.
“Hanya diberi ikat kepala hijau bertuliskan huruf Arab agar terlihat seperti anggota ormas Islam,” ungkapnya.
Deklarasi Ciganjur pada 10 November 1998 yang digaungkan empat tokoh, yakni Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amien Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X turut mempersoalkan keberadaan Pam Swakarsa yang ikut mengamankan aksi bersama TNI/Polri. Mereka menuntut pasukan tersebut membubarkan diri.
Namun, bentrokan memuncak tiga hari berselang. Pada 13 November 1998, aparat menembak secara membabi buta ke arah mahasiswa. Mengutip data Amnesty Internasional, sebanyak 17 warga sipil tewas dan 109 lainnya terluka dalam insiden ini.
Bertubi-tubi
Kendati polisi berdalih bahwa citra Pam Swakarsa kali ini berbeda jauh dengan kelompok pengamanan di tahun 1998 lalu, pegiat sipil kadung gerah dengan wacana tersebut. Karena bukan kali ini saja gendang militerisasi sipil dibunyikan.
Awal tahun ini juga terbit Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelaksanaan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Yang dipersoalkan dari aturan ini adalah pembentukan Komponen Cadangan.
Pemerintah menganggap penting keberadaan komponen cadangan guna mengantisipasi keterbatasan jumlah personel TNI. Terutama perihal memastikan kesiapan negara menghadapi ancaman keamanan di masa depan. Namun, alasan itu ditolak para pegiat sipil.
“Kepangkatan Komcad (komando cadangan) ini kian melegitimasi militerisasi sipil. Sebab, Komcad telah mengadaptasi garis komando militer ke dalamnya,” ujar Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, Jumat (22/1/2021) mengutip CNN Indonesia.
Kontroversi serupa juga muncul pertengahan tahun 2020 lalu. Kementerian Pertahanan ketika itu mulai menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar para mahasiswa yang duduk di bangku perkuliahan dapat mengikuti program bela negara. Setelah universitas, program itu akan masuk pula ke sekolah.
Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam mengatakan, pendidikan bela negara masuk melalui skema Kampus Merdeka yang telah berjalan sejak awal 2020. Ia mengutip ujaran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
“Nanti mahasiswa yang mengikuti program komponen cadangan selama 10 bulan saat lulus sarjana sekaligus mendapatkan pangkat perwira cadangan,” kata Nizam.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta memastikan penyelenggaraan program bela negara di perguruan tinggi memang diperlukan, tapi bukan berbentuk pendidikan militer.
"Untuk mendaftar menjadi komponen cadangan sifatnya harus sukarela. Pemaksaan di sini bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia," ujarnya, mengutip Katadata, Agustus 2020 lalu.
Program ini menuai kritik dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyebut pendidikan militerisme dalam ranah pendidikan formal berbahaya. Pemerintah seolah memelihara kultur kekerasan.
Ia juga melihat ada upaya pemerintah meredam sikap kritis mahasiswa terhadap negara. “Upaya-upaya kritis, dari anak muda khususnya, itu mulai dibungkam secara perlahan lewat wajib militer ini," kata Fatia.
Direktur Imparsial, Al Araf telah mewanti-wanti jauh sebelum UU PSDN disahkan. Ia mengatakan, pelibatan warga sipil sebagai komponen cadangan dalam menghadapi ancaman non militer dapat menimbulkan masalah serius dalam tata kelola keamanan di Indonesia.
“UU ini melegalisasi suatu proses militerisasi sipil yang juga dapat digunakan untuk menghadapi kelompok-kelompok dalam masyarakat di negeri sendiri sehingga rentan memicu konflik horizontal,” tulis Al Araf di Kompas, November 2019.
Menurut dia, tanpa adanya aturan yang rinci dalam pelibatan warga sipil, UU ini dapat digunakan untuk menghadapi kelompok masyarakat sipil lainnya yang kritis dengan dalih demi kepentingan keamanan.
Serangkaian upaya pemerintah yang tampak bertubi-tubi menyisipkan agenda pengamanan hingga militerisme ke ranah sipil, tentu memantik sejumlah dugaan. Namun menarik jika salah satunya menyoroti soal rekam jejak relasi sipil dan militer di Indonesia.Perpecahan di Masyarakat
Potret berbaurnya militerisme ke ranah sipil sebenarnya bukan cerita baru. Saafroedin Bahar dalam Kajian Awal Keterkaitan Pasukan Paramiliter dan Militer dengan Faham Militerisme dan Fasisme di Indonesia (Jurnal Ketahanan Nasional, Desember 2000) menarik sejarah militerisasi sipil sejak masa kemerdekaan.
Saat itu berbagai partai politik lazim membentuk pasukan paramiliternya sendiri. Bukan lagi untuk tujuan kemerdekaan, melainkan sebagai kelompok penekan untuk mencapai tujuan politik mereka.
“Peran mereka, salah satunya menekan pers yang memberitakan hal-hal yang dinilai merugikannya, parpol yang didukungnya, atau bahkan tokoh idola mereka,” ujar Saafroedin.
Sementara itu, Zen RS dalam ulasan Menjadi Republik Ormas, Membiakkan Paramiliter di Tirto, Januari 2017 menyulam kembali lembaran buram relasi sipil-militer sejak masa revolusi silam.
Berturut-turut, dari program resmi negara semisal Pembela Tanah Air (PETA), lalu pendirian Corps Suka relawan untuk kampanye Dwikora, hingga model ‘sokongan setengah terbuka’ dari militer Indonesia ke sejumlah faksi-faksi anti-komunis di tahun 1965.
Tak hanya itu, sejarah pembentukan milisi di daerah konflik, seperti Irian Jaya, Timor Timur dan Aceh juga penting menjadi catatan, terutama soal dampak militerisasi sipil yang justru memperparah konflik dan membekas lama di masyarakat.
Di Aceh, riwayat militerisasi sipil salah satunya ditoreh pada jejak konflik horizontal yang berkecamuk di kawasan tengah Aceh. Padahal, daerah ini sejak dulu terbilang harmonis dihuni masyarakat yang heterogen. Ada tiga etnis dominan yang mendiami wilayah dataran tinggi ini: etnis Gayo, Aceh dan Jawa.
Namun, operasi militer sejak tahun 1989 yang berkembang pesat di wilayah pesisir Aceh, perlahan merebak ke daerah itu. Laporan Majalah Tempo, Mayat-mayat di Tanah Gayo, Juli 2001 silam menulis, “kancah peperangan telah merembet ke Aceh Tengah”.
Dugaan itu menyusul lonjakan jumlah korban tewas akibat konflik di Gayo yang mencapai 148 jiwa, hanya dalam tempo sebulan. Area konflik melebar karena sebagian gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka yang ada di Aceh Utara mulai terdesak, lalu masuk ke Aceh Tengah.
“Setelah dua tahun Aceh bergolak, baru September (2000) lalu ketenangan di daerah sejuk ini terobek,” tulisnya.
Intensitas konflik meningkat kemudian. Hal ini diperparah kemunculan kabar bahwa militer diam-diam mengorganisir penduduk sipil menjadi garda sukarela yang pro-Jakarta. Bibit milisi tumbuh di situ, menyela benturan langsung antara militer Indonesia dan kelompok GAM. Tempo mengungkap dugaan TNI/Polri mengajari warga merakit senjata api dan membekalinya dengan pelatihan militer.
Dugaan serupa juga pernah diutarakan Koordinator Aceh Working Group (AWG), Rusdi Marpaung, 2006 silam. Ia membeberkan, proses pembentukan kelompok milisi di Gayo tidak terlepas dari keterlibatan negara. Tentara merekrutnya dari sejumlah desa, lalu melatih dan mempersenjatai mereka untuk ikut melawan GAM.
Meskipun militer saat itu menyangkal telah membentuk dan melatih laskar partikelir itu, namun mereka mengakui kelompok ini bagian dari pasukan pengamanan swakarsa. “Itu inisiatif mereka sendiri, sejak Operasi Cinta Meunasah,” ucap Letkol Rochana Hardiyanto yang saat itu menjabat Komandan Distrik Militer Aceh Tengah.
Operasi Cinta Meunasah adalah salah satu operasi yang digelar di Aceh pasca pencabutan Daerah Operasi Militer pada 1998. Operasi ini efektif pada 18 Agustus 2000 sampai 18 September 2001.
Keberadaan milisi untuk menekan GAM lantas memicu benturan etnis, seiring santernya dugaan bahwa sebagian besar komponen milisi terdiri dari warga pendatang Jawa. Syak wasangka tak terhindarkan, antara warga etnis Aceh dan Gayo di satu pihak, dan pendatang Jawa di lain pihak.
“Hal ini menyebabkan interaksi antar etnis yang awalnya terjalin harmonis, lalu memburuk, dan terjebak pada konflik bertahun-tahun,” ujar Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra kepada readers.ID.
Butuh waktu lama untuk memulihkan kondisi sosial yang sempat dibekap perpecahan saat konflik. Apalagi pasca perjanjian damai di Aceh, isu etnis justru sering dieksploitasi untuk kepentingan elektoral di daerah itu.
“Penting untuk meretas jalan rekonsiliasi, baik dari kalangan mantan GAM maupun Pembela Tanah Air (PETA) di Gayo agar sentimen tak merambah kemana-mana,” ujarnya lagi.
Sejak tahun 2009, warga perempuan di Bener Meriah difasilitasi sejumlah lembaga sipil lokal mulai menjajaki upaya damai. Pertemuan informal itu bermuara pada pembentukan Kelompok Perempuan Cinta Damai.
“Dulu sering saling mencela antar etnis. Namun sejak bergabung dengan kelompok ini kami menyatu bagaikan satu etnis, tidak ada lagi perbedaan,” kata Maimunah dari Desa Kenawat, Redelong kala itu. Di lingkup komunitas, jalan rekonsiliasi memang menemukan titik terang.
Cerita inisiatif masyarakat di Bener Meriah ini juga, menurut Hendra Saputra, harusnya dirawat terus menerus terutama oleh pemangku kepentingan di sana. Ia mengungkit momen tiga tahun sebelum KPCD didengungkan. Para pentolan dari masing-masing kubu yang bertikai dalam konflik sepakat mengikrarkan Musara Pakat Redelong, 28 Juli 2006.
“PETA dan GAM sudah saling berangkulan,” aku Misriadi alias Adijan, salah satu tokoh Front Perlawanan Separatis, dalam laporan bertajuk Baru Sebatas Rangkulan di Tempo, 2006.
Para tokoh lainnya di bumi Gayo menunjukkan optimisme serupa. Meskipun jauh di kawasan pantai timur dan utara Aceh, hubungan bekas gerilyawan dan front kala itu masih dingin. Tapi setidaknya inisiatif rekonsiliasi pernah muncul.
“Masyarakat di Gayo sebenarnya sangat resisten terhadap konflik, mereka telah hidup rukun sejak dulu di lingkungan yang heterogen. Perlu melihat aspek kearifan lokal untuk merajut perdamaian yang utuh di sana,” sambung Hendra.
Di tengah-tengah segelintir masyarakat yang tertatih memulihkan kondisi usai perpecahan, seiring waktu pula, militerisme tetap menemukan celahnya merasuki ranah sipil. Ingatan dampak konflik horizontal tinggal cerita. Beranjak tahun, rupa militerisasi sipil makin beragam, namun dengan mara laten yang masih sama.
“Setelah Orde Baru runtuh, jamur kelaskaran macam itu malah makin membiak dengan warna yang kembali beragam,” tulis Zen RS.
Pam Swakarsa salah satu warisannya. Kendati tak lagi identik dengan penampilan bergaya militer, kelompok-kelompok di era ini muncul dengan simbol-simbol politik identitas. Bisa berupa corak kedaerahan, etnis maupun agama.Loyalis Buta
Dinamika positif hubungan sipil-militer di Indonesia, sedikit banyaknya ditentukan oleh seberapa jauh inisiatif kepemimpinan sipil mampu mengarahkan militer agar tetap profesional. Artinya, militer fokus pada tugas pertahanan negara dan tidak mencampuri urusan politik. Koesnadi Kardi dalam Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia (Jurnal Sosiologi Fisip Universitas Indonesia, 2014) menilai, ide reformasi militer saat ini cenderung stagnan.
Penyebabnya, kata dia, selama ini institusi sipil terjebak pada cara pandang historis, bahwa militer sudah biasa berada di sistem pemerintahan, terutama di masa orde baru yang terkenal dengan kebijakan Dwifungsi-nya. Sehingga sipil lupa pada peran dan fungsi sebenarnya dari militer itu sendiri.
“Sipil tak kunjung beranjak melalui konsep modern, yang didasarkan pada kompetensi militer dalam penggunaan instrumen koersif,” terang Koesnadi.
Secara politik, menurutnya cara pandang semacam ini bisa menimbulkan kerawanan. Sementara secara sosiologis, keadaan tersebut tak akan berubah selama institusi-institusi sipil belum punya pemahaman yang sama soal peran ideal militer. Dalam penelitiannya, Koesnadi bahkan mendapati alasan paling mencolok dari institusi sipil yang mengikutsertakan militer untuk terlibat dengan kerja mereka, yakni untuk menunjang nilai kedisiplinan.
“Kebiasaan ini muncul karena adanya paradigma yang menganggap militer telah memiliki etos kerja yang lebih baik daripada sipil,” ujarnya.
Namun, tanpa harus terlibat secara langsung pun, militerisme juga telah menyelapi alam pikir masyarakat lewat narasi tunggal sejarah versi penguasa sejak dulu. Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan A Laksamana dalam Politik Sejarah Militer (Kompas, 2016) mengutip Katharine McGregor, bahwa penulisan sejarah Indonesia sejak masa Soekarno hingga Soeharto lebih mengarah pada semangat membangun nasionalisme, ideologi serta kepentingan politik rezim, bukan sebagai pembelajaran keilmuan sosial dan humaniora.
“Apalagi sejarah politik Indonesia sejak tahun 1950-an sangat terkait dengan institusi militer. Artinya, jika ada politisasi sejarah politik oleh pemerintah atau elite penguasa, maka sejarah militer pun dapat ikut terpolitisasi,” tulisnya.
Sementara itu, Saafroedin mengutip Alfred Vagts (1959), bahwa gejala militerisme merupakan tipikal negara fasisme seperti di Jerman dan Italia sebelum perang dunia ketiga. Ia mengistilahkan militarism of the civilians atau militerisme orang-orang sipil.
Gejala ini, menurutnya tak lepas dari masalah personalisme seorang pemimpin yang menggiring loyalitas tanpa batas. Orientasi semacam ini biasanya muncul ketika masyarakat terjebak pada situasi sosial, ekonomi maupun politik yang tidak pasti. Sehingga massa membutuhkan pegangan tegas dari seorang tokoh yang mereka anggap benar.
Di sisi lain, persepsi itu justru menjadi hambatan dalam mewujudkan demokrasi. Tumpuan keputusan politik di tangan segelintir tokoh elite menjadikan massa mudah diarahkan sesuai kepentingan tertentu.
“Selama persepsi ini ada, massa akan terus dikuasai para elite,” imbuh Saafroedin.
Di Indonesia, gejala militerisme bisa menggerogoti golongan mana pun. Bahkan, kata dia, di bawah tokoh-tokoh tertentu, beberapa organisasi keagamaan atau yang secara eksplisit menyatakan diri berjuang demi demokrasi, ironisnya acap menjelma menjadi kelompok fasis dan militeristik.
Bagi Saafroedin, fenomena ini menarik. Banyak tokoh sipil yang dengan lantang menyatakan penolakan terhadap fasisme saat mereka belum berkuasa. Namun ketika sudah memegang tampuk kekuasaan itu, mereka malah berlaku sama. Lalu nanti akan muncul kelompok lain yang menentang cara mereka berkuasa.
“Sejarah politik Indonesia modern terus berulang dalam siklus yang tak berujung,” ketusnya.
Agaknya, pengaktifan Pam Swakarsa setelah tidur panjang selama dua dekade silam adalah bagian dari siklus tersebut.[acl]

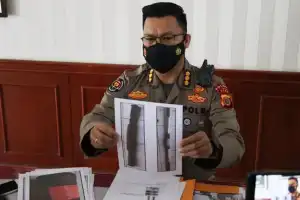

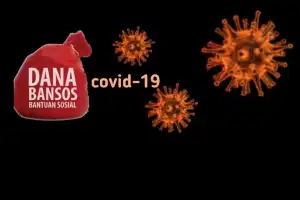



Komentar