HARI PAHLAWAN
Mengenal 5 Sosok Pahlawan Perempuan Aceh

Pada setiap 10 November sejatinya diperingati hari Pahlawan Nasional Indonesia. Mereka telah berjuang dalam memperjuangkan dan membela negara, wilayah dari segala bentuk.
Di Aceh terdapat sejumlah tokoh pahlawan perempuan yang bangkit di setiap fase yang berbeda. Kemudian sebagian besar di antaranya sudah dinobatkan menjadi pahlawan Nasional oleh pemerintah RI dan sebagian yang lain tidak mendapatkan surat.
Sejumlah tokoh perempuan Aceh tersebut adalah seperti Cut Nyak Dhien, Pocut Meurah Intan, Cut Meutia, Laksamana Malahayati dan Qurrata 'Aini atau Datu Beru. Berikut catatan sejumlah tokoh perempuan yang dilansir dari berbagai sumber.
Cut Nyak Dhien
Nama Cut Nyak Dhien tentu tidak asing lagi ditelinga masyarakat Aceh dan bahkan nasional. Ia merupakan sosok perempuan yang sangat ditakuti Belanda, karena kiprahnya mempengaruhi banyak masyarakat untuk berjuang.
Cut Nyak Dhien lahir di kampung Lam Padang Peukan Bada, wilayah VI Mukim, Aceh Besar pada tahun 1848. Ia merupakan keturunan bangsawan Aceh dari darah daging Teuku Nanta Setia. Pada umur 12 tahun, ia kemudian dinikahkan dengan Teuku Ibrahim Lam Nga putra dari Teuku Po Amat, Uleebalang Lam Nga XIII.
Munculnya semangat juang Cut Nyak Dhien dimulai pada umur 27 tahun yaitu pada 1975 setelah menikah dengan Teuku Ibrahim Lam Nga periode (1962-1878). Ia harus berjuang mengurusi anak sendirian tanpa pendampingan suami karena pergi berjuang mengusir penjajah Belanda. Secara tidak langsung saat inilah bintik-bintik semangat juang Cut Nyak Dhien mulai tumbuh berkobar secara perlahan.
Pada 29 Juni 1878, Teuku Ibrahim Lam Nga syahid di Glee Tarun. Kondisi ini menjadi sumber kekuatan bagi Cut Nyak Dhien untuk bangkit berjuang melawan Belanda menggantikan suaminya. Dua tahun berselang, Cut Nyak Dhien kembali dipersunting oleh Teuku Umar pada 1880.
Dari pernikahannya lahir seorang putri bernama Cut Gambang. Namun enam tahun kemudian, Teuku Umar tewas dalam pertempuran sengit dengan Belanda di Suak Ujong Kalak, Meulaboh, Aceh Barat, pada 11 Februari 1899.
Menghadapi situasi itu, Cut Nyak Dhien mengajak semua masyarakat untuk berjuang mengusir Belanda sehingga memiliki banyak pengikut.
Polarisasi perjuangan yang ditanamkan kepada masyarakat inilah yang membuat Belanda semakin takut. Cut Nyak Dhien akhirnya menerapkan strategi perang gerilya dari hutan ke hutan hingga enam tahun lamanya.
Namun sayang, perjuangannya itu membuat kondisi kesehatannya menurun karena mengidap penyakit encok dan mata rabun. Cut Nyak Dhien akhirnya ditangkap pada 4 November 1905 dan kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat.
Di Sumedang, dirinya aktif memberikan kebermanfaatan dengan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat sekitar Paya Kumbuh, Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak Dhien kemudian berpulang kepangkuan Sang Penguasa pada 06 November 1908.
Pocut Meurah Intan
Pocut Meurah Intan dikenal gigih dan kuat dalam mengusir Belanda dari Bumi Aceh sehingga ia dijuluki sebagai “Most Wanted Person” oleh sekutu Belanda. Pocut Meurah Intan merupakan keturunan bangsawan kerajaan Aceh. Ia lahir di Tuha Biheue, Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh. Ayahnya Teuku Meurah Intan seorang hulubalang atau Keujruen Biheue, dari keturunan Pocut Bantan.
Pocut Meurah Intan juga dikenal dengan nama Pocut Di Biheue yang berarti Pocut dari Biheue. Biheue merupakan sebuah negeri yang pada masa Kesultanan Aceh berada di bawah wilayah Sagi XXXI Mukim, Aceh Besar.
Ia kemudian menikah dengan Tuanku Abdul Majid, seorang putra Tuanku Abbas bin Sultan Alaiddin Jauhar Alam Syah. Bersama suaminya Tuanku Abdul Majid, ia dikenal sebagai tokoh dari Kesultanan Aceh yang paling anti dengan Belanda.
Sebagai penentang Belanda, Tuanku Abdul Majid tidak mau berdamai dengan Belanda. Ia gigih dan geliat melawan Belanda di Selat Malaka sekitar Laweung dan Batee, yang kerap menyerang kapal-kapal dari maskapai berbendera Belanda.
Sejarah mengulas, perjuangan keras terakhir dari Pocut Meurah Intan terjadi pada akhir abad 19 dan pada awal abad 20. Bertepatan pada 11 November 1902, ia dikepung oleh 17 serdadu khusus Belanda dari Koprs Marchausse di Biheu yang dipimpin Veltman. Karena dalam keadaan genting, Pocut melawan Belanda dengan sebilah rencong di tangan.
Pada pertempuran sengit itu, Pocut Meurah Intan mengalami banyak luka pada bagian kepala, dua di bahu, satu urat kening dan otot tumitnya putus dan terbaring lemah penuh dengan darah dan lumpur.
Semangat kuat dan pantang menyerahnya inilah justru menjadi tantangan bagi Belanda dan membuat mereka kagum hingga Veltman, pimpinan Korps Marcchausse menyebutnya Heldhafting (Yang Gagah Berani).
Meski terbaring lemah dan tak berdaya, Veltman mengira dengan keadaan Pocut yang lemah akan kehabisan darah dan bakalan meninggal dunia, sehingga Belanda membiarkannya terbaring ditanah bersimbah darah itu. Namun perkiraan Veltman salah, Pocut waktu itu kemudian melarikan diri setelah Belanda pulang.
Mendengar Pocut masih hidup di telinga Veltman, ia kemudian berkunjung dan menawari Pocut untuk dirawat oleh dokter utusan Veltman. Namun pocut menolak itu. Tapi Veltman merasa iba hingga terus-menerus menawarkan dan mengajak Pocut agar mau dirawat oleh Belanda. Akhirnya Pocut menerima bujukan Veltman ini dengan syarat, dokter yang merawatnya adalah tentara Belanda pribumi.
Pada 1905, Pocut Di Biheue kemudian ditangkap di Kutaraja (saat ini Banda Aceh) beserta anak dan anggota keluarga kesultanan. Penangkapan itu berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda, tertanggal 6 Mei 1905, No. 24. Maka disinilah titik akhir dari perjuangan Pocut Meurah Intan beserta anak-anaknya, yakni Tuanku Budiman dan keluarga kesultanan Tuanku Ibrahim. Mereka kemudian diasingkan keluar Aceh tepatnya di Blora, Jawa Tengah.
Pocut menjadi orang kedua dilakukan pengasingan setelah anaknya bernama Tuanku Muhammad diasingkan ke Tondano Sulawesi Utara pada tahun 1900 oleh Belanda. Dari tahun 1905 hingga 1937, pejuang perempuan dari Aceh ini terus mengalami gangguan kesehatan. Hingga akhirnya pada 19 September 1937, Pocut Meurah Intan berpulang ke rahmatullah di Blora dan dimakamkan di sana.
Saat ini Makam Pocut Meurah Intan berada di desa Temurejo, atau sekitar 5 km arah utara alun-alun kota Blora. Pada tahun 2001, Pemerintah Aceh sempat merencanakan untuk memindahkan jasad Pocut Meurah Intan ke Aceh. Namun rencana itu ditolak oleh pihak keluarga melalui wasiat Pocut kepada RM Ngabehi Dono Muhammad. Pocut menginginkan dan lebih suka dikebumikan di Blora, Jawa Tengah.
Cut Meutia
Cut Nyak Meutia lahir pada 15 Februari 1870. Ia merupakan pahlawan nasional Indonesia dari Aceh berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 107/1964 pada tahun 1964.
Cut Nyak Meutia atau Cut Meutia merupakan anak dari Teuku Ben Daud Pirak dengan Cut Jah. Orang tua Cut Nyak Meutia merupakan keturunan asli Aceh seorang Uleebalang di desa Pirak yang berada dalam daerah Keuleebalangan Keureutoe.
Cut Meutia memiliki empat saudara kandung dan dirinya merupakan putri satu-satunya dari pasangan Teuku Ben Daud dan Cut Jah, sementara keempat saudaranya adalah laki-laki. Saudara tertua bernama Cut Beurahim disusul Teuku Muhammadsyah, Teuku Cut Hasen dan Teuku Muhammad Ali.
Pertempuran awal Cut Meutia terhadap Belanda dimulai bersama sang suami Teuku Muhammad atau Teuku Tjik Tunong. Namun pada bulan Maret 1905, Tjik Tunong berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati di tepi pantai Lhokseumawe.
Sebelum meninggal, Teuku Tjik Tunong berpesan kepada sahabatnya Pang Nanggroe agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya Teuku Raja Sabi.
Cut Meutia kemudian menikah dengan Pang Nanggroe sesuai wasiat suaminya dan bergabung dengan pasukan lainnya di bawah pimpinan Teuku Muda Gantoe.
Pada suatu pertempuran dengan Korps Marechausée di Paya Cicem, Cut Meutia dan para wanita melarikan diri ke dalam hutan. Pang Nanggroe sendiri terus melakukan perlawanan hingga akhirnya tewas pada 26 September 1910.
Cut Meutia kemudian bangkit dan terus melakukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukannya. Ia menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju wilayah Gayo melewati hutan belantara.
Namun pada 24 Oktober 1910, Cut Meutia bersama pasukannya bertempur dengan Marechausée di Alue Kurieng hingga membuat Cut Nyak Meutia gugur dan kemudian dimakamkan di Alue Kurieng, Aceh.
Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya, Pemerintah Republik Indonesia mengabadikannya dalam pecahan uang kertas rupiah baru Republik Indonesia, pecahan Rp1.000.
Laksamana Malahayati
Laksamana Malahayati merupakan pahlawan wanita dari Aceh. Dia lahir di Aceh besar, pada tahun 1550. Laksamana Malahayati merupakan putri dari Laksamana Mahmud Syah, cucu Laksamana Said Syah, dan cicit dari Sultan Aceh Salahudin Syah yang berkuasa 1530-1539.
Dari silsilahnya ini Malahayati mewarisi semangat wira samudra, di mana ia terlibat aktif dalam pertempuran Teluk Haru melawan armada laut Portugis. Pertempuran tersebut menewaskan suaminya, namun dia tidak larut dalam kesedihan, bahkan bangkit membentuk pasukan Inong Balee yang terdiri dari para janda yang suaminya gugur dalam perang.
Dalam Inong Balee ini, Malahayati diangkat sebagai laksamana, sekaligus menjadikannya wanita Aceh pertama yang menyandang pangkat laksamana. Pada 21 Juni 1599, Laksamana Malahayati memimpin pasukan laut Kesultanan Aceh melawan Belanda yang memaksakan kehendak dalam berdagang dengan Aceh.
Sejarah mencatat, pertempuran ini menewaskan Cornelis De Houtman, pelaut Belanda yang menemukan jalur menuju Indonesia. Laksamana Malahayati meninggal dunia tahun 1615, dalam usia 65 tahun. Makamnya saat ini ada di Desa Lamreh, Krueng Raya, Aceh Besar. Laksamana Malahayati ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tanggal 6 November 2017.
Qurrata 'Aini/ atau Datu Beru
Nama Qurrata ‘Aini perempuan asal dataran tinggi Gayo mungkin belum banyak dikenal dalam sejarah para pahlawan wanita di Aceh, meski di Gayo namanya sangat familiar.
Dalam catatan sejarah Aceh, namanya memang tidak begitu familiar namun dinilai perempuan ini sejajar dengan tokoh sekelas Tjoet Nya’ Dien, Tjut Mutia maupu Laksamana Malahayati.
Qurrata ‘Aini diperkirakan lahir antara 1490-1514. Tidak banyak catatan literatur kapan ia lahir, namun dalam sejarah-sejarah yang ditulis, saat dirinya sudah dewasa, ia pernah menjadi utusan utusan Reje Linge atau Kerajaan Islam Lingga di Gayo sebagai perwakilan parlemen pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam (satu-satunya perempuan) pada masa Kesultanan Ali Mughayatsyah dari tahun 1514 sampai dengan 1530.
Datu Beru sendiri melekat pada diri perempuan bernama asli Qurrata ‘Aini ini konon karena sampai akhir hayatnya, ia tetap berstatus sebagai gadis (dalam bahasa Gayo disebut Beru) karena hingga akhir hayatnya menyandang seorang gadis, hingga masyarakat menjulukinya sebagai Datu.
Sejarawan Aceh asal Gayo, Yusra Habib Abdul Gani yang kini berdomisili di Denmark menyebutnya Qurrata ‘Aini adalah seorang tokoh wanita Aceh yang sejak kecil sudah melekat ciri-ciri kepemimpinan dan pembela kebenaran.
Qurrata ‘Aini sangat cerdas, menguasai ilmu agama, politik, falsafah dan hukum, pandai beragam bahasa termasuk, Aceh, Arab dan Melayu.
Prestasi gemilangnya, sempat menggemparkan dunia pradilan Aceh pada ketika itu, hanya saja tidak diketahui secara meluas, karena kurangnya minat para pakar sejarah khususnya dari Gayo untuk meneliti dan menulis demi memperkaya khazanah sejarah Aceh.
Yusra Habib menuturkan bahwa Qurrata ‘Aini punya “warna” lain dalam berkiprah di dunia hukum, politik dan pemerintahan kerajaan Aceh pada masa itu. Datu Beru menjadi satu-satunya wanita Aceh yang mampu menduduki kursi Parlemen pusat pada masa pemerintahan Sultan Ali Mughayatsyah.
Dalam satu kesempatan, Qurrata ‘Aini dimintai pertimbangan oleh Sultan Aceh dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan yang melibatkan salah seorang putra Raja Linge yang saat itu hukum yang diterapkan di kerajaan Aceh adalah hukum Islam.
Setiap pelaku pembunuhan yang telah terbukti melakukan tindakan pembunuhan, wajib dihukum Qisash (hukman mati). Namun pada waktu itu Qurrata ‘Aini memberi pertimbangan.
Ia berdalih bahwa dalam Al Qur’an pun telah disebutkan bahwa hukum qisash bisa gugur jika ahli waris korban mau memaafkan si pelaku.
Pelaku akhirnya hanya dihukum membayat diyat (denda) kepada ahli waris dan menjalani hukuman adat. Tapi justru dengan hukuman adat tersebut menjadi efek jera bagi pelaku, karena hukuman adat sejatinya menimbulkan beban psikologis yang sangat berat bagi pelaku.
Pada waktu itu Qurrata ‘Aini berprinsip bahwa hukuman mati bukanlah sebuah solusi, karena dengan hukuman mati seseorang tidak akan bisa lagi memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukannya.
Meski demikian, pertimbangan hukum Datu Beru tetap tidak melanggar aturan yang tercantum dalam Al Qur’an yang menjadi kitab hukum yang berlaku di kerajaan Aceh pada masa itu.
Sejak kejadian itu, nama Datu Beru semakin dikenal sebagai ahli dan pakar hukum baik secara syariat maupun secara adat. Posisi Datu Beru sebagai satu-satunya perempuan yang menguasai hukum, membuat dirinya sangat disegani di kalangan kerajaan.
Menjadi seorang pakar hukum dan anggota parlemen kerajaan bagi perempuan pada masa itu bukanlah hal yang lazim, namun ia dapat menjalani peran tersebut dengan baik di tengah dominasi kaum pria pada waktu itu.
Demikianlah sejumlah tokoh perempuan Aceh yang pernah menjadi warna bagi sejarah Aceh di masa lalu. Semoga bermanfaat.









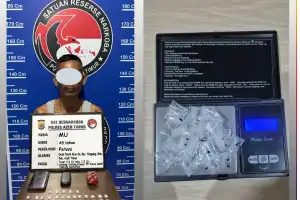

Komentar