Dewan Atsiri Indonesia Gandeng ARC-USK Bikin Pelatihan Nilam Nasional
“Tidak mungkin komoditas dapat bertahan sekian ratus tahun jika komoditas itu tidak benar-benar dibutuhkan dan memiliki keunikan.”
 Foto: for Readers.id
Foto: for Readers.idGEDUNG Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh menjadi tempat menuntut ilmu bagi pelaku industri nilam se-Indonesia pada Sabtu, 27 April 2024.
Oleh Dewi Suryani Sentosa
Betapa tidak. Acara pelatihan berbisnis minyak nilam dengan tema "Prospek Pengembangan Nilam dari Hulu hingga Hilir" berhasil mengumpulkan para pemangku kepentingan terkemuka dalam industri atsiri Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang berharga.
Peserta yang hadir terdiri dari anggota Dewan Atsiri Indonesia (DAI) dan perwakilan dari 20 perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang atsiri.
Sejumlah perusahaan itu antara lain Delta Atsiri Prima, PT Inti Agro Solution, PT Jeeva Aroma Nusantara, Indika Multi Properti, PT Alam Indonesia, dan banyak lagi. Mereka saling berbagi wawasan dan pengalaman, menandai semangat kolaboratif dalam industri ini.
Dihadiri oleh Dewan Atsiri Indonesia, acara ini merupakan kolaborasi antara Atsiri Research Center-Universitas Syiah Kuala (ARC-USK) dan dukungan dari International Labour Organization.
Dr Syaifullah Muhammad ST Meng, Kepala Atsiri Research Center menjadi pembicara dalam acara pelatihan tersebut.
"Kesatuan visi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam industri atsiri menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam pengembangan industri nilam secara menyeluruh," ujar Dr Syaifullah.
Dia memaparkan, perjalanan penelusuran nilam membawa kita menelusuri jejak sejarah perdagangan Belanda yang kaya.
Saat bisnis gula mengalami penurunan di Belanda, menyebabkan penurunan harga gula secara global, sehingg para pelaku perdagangan mencari komoditas alternatif.
Inilah yang mendorong penemuan komoditas seperti kopi dan nilam, yang pada akhirnya membawa kita kepada penemuan nilam di Tapaktuan.
Bukti sejarah menunjukkan adanya jejak keberadaan pabrik Belanda di Tapaktuan, yang menjadi bukti konkret keterlibatan Belanda dalam perdagangan nilam.
Penelusuran yang dilakukan Atsiri Research Center (ARC) bertujuan untuk mengungkap asal-usul sebenarnya dari nilam.
Salah satu literatur menyebutkan kata “nilam” berasal dari akronim NILAM (Netherland Indiche Landbow Acheh Maatchapij), sementara literatur lain menyatakan nilam diangkut oleh Netherland Indiche Landbow Maatchapij (NILM).
Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan nilam pada masa itu banyak terkait dengan perusahaan Belanda.
Bahkan, bukti-bukti sejarah yang terdapat dalam literatur di museum Belanda menunjukkan keberadaan produk seperti Aceh Patchouli Oil, yang menegaskan peran penting Aceh dalam perdagangan nilam pada masa tersebut.
Dr Syaifullah menjelaskan, “Tidak mungkin komoditas dapat bertahan sekian ratus tahun jika komoditas itu tidak benar-benar dibutuhkan dan memiliki keunikan.”
Keunikan Nilam Aceh terletak pada aspek komposisi kimia yang unik, yaitu memiliki komponen minor yang tidak ditemukan pada varietas nilam di daerah lain.
Faktor-faktor lingkungan seperti kelembapan, suhu, dan intensitas cahaya matahari yang khas di wilayah Aceh turut berperan dalam membentuk karakteristik khusus dari nilam yang ditanam di daerah tersebut.

Potensi ekonomis dari nilam ini sangat besar, mengingat lebih dari 50% komponen kimianya dapat memberikan nilai tambah yang signifikan jika dimanfaatkan dalam industri pengolahan.
Konversi nilai ekonomi dari minyak nilam dapat ditingkatkan melalui strategi purifikasi yang merupakan rahasia dalam pengembangan produk turunan.
Hal ini disebabkan oleh keberadaan zat-zat pengotor yang tidak diinginkan dalam minyak nilam mentah, sehingga perlu proses ekstraksi dan purifikasi sebelum minyak tersebut dapat digunakan dalam pembuatan produk parfum, misalnya.
Melalui tahap-tahap ini, nilai ekonomi minyak nilam dapat meningkat signifikan, mencapai 397%, sehingga menjadikan sektor produk turunan sebagai pilihan menarik dalam pengembangan industri nilam.
Secara konseptual, periode tanam optimal untuk tanaman nilam adalah sekitar 3 tahun. Namun, untuk mencapai produktivitas yang optimal, perlu dilakukan intervensi dalam manajemen tanah, salah satunya dengan menerapkan pembuatan rumah kompos untuk mengimplementasikan konsep sirkular ekonomi.
Keterlibatan ini dianggap penting karena merusaknya kondisi lingkungan, seperti kekeringan tanah dan gangguan terhadap sumber air yang disebabkan penyerapan nutrien oleh tanaman, dapat menghambat akses pembeli internasional terhadap produk nilam.
Untuk memastikan kesinambungan bisnis dalam konteks ini, prinsip keadilan menjadi krusial. Keadilan di sini mengacu pada penegakan hak setiap pihak yang terlibat, termasuk petani, dan penekanan terhadap keserakahan yang dapat mengganggu proses produksi dan distribusi.
Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap aspek ini sangatlah penting. Terdapat dorongan untuk memastikan setiap tahap dalam rantai nilai menghasilkan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat.
Tantangan awalnya adalah ketidakpercayaan terhadap mekanisme pasar. Namun dengan strategi penta helix approach dengan melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan kini juga media, tantangan tersebut dapat diatasi.
Kolaborasi antara semua pihak terlibat, melalui pendekatan penta helix, telah membawa kemajuan yang nyata dalam industri nilam Aceh.
Dengan semakin terbukanya peluang pasar internasional, produk-produk turunan nilam dari Aceh memiliki daya kompetisi yang baik, membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat.
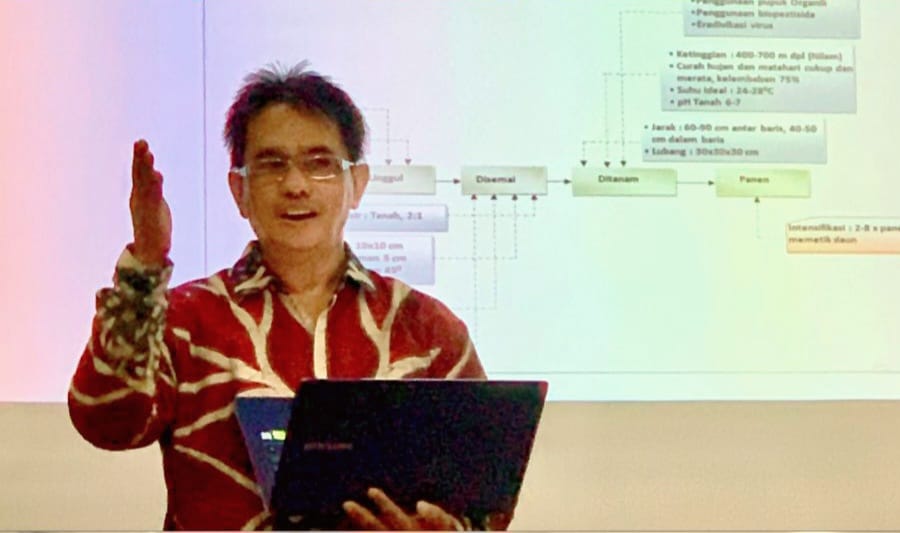
Syaifullah mengungkapkan, sejak tahun 2015, hanya 4 kabupaten di Aceh yang menanam nilam, tetapi kini jumlahnya sudah bertambah mencapai 17 kabupaten.
Sekarang Indonesia memasok 90% nilam dunia. Ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki Aceh dalam industri nilam.
Inisiatif pun dilakukan seperti pendirian NINO PARK (Nilam Innovation Park), dengan dukungan dari Bank Indonesia. Dibangun untuk membantu masyarakat dalam menanam nilam. Sementara strategi pengembangan industri nilam dilakukan dari berbagai aspek, dari hulu ke hilir, dan dari bahan baku hingga pemasaran ke Prancis.
“Dengan berbagai inovasi dan strategi yang diterapkan, Aceh mampu meningkatkan produksi nilamnya dari 150 ton per tahun pada 2016 menjadi 350 ton per tahun pada tahun terakhir," papar Syaifullah.
Dalam konteks ini, Ketua ARC-USK juga menggarisbawahi pentingnya peran universitas dalam mendukung petani nilam Aceh.
Universitas dianggap sebagai sumber inovasi dan pengetahuan yang dapat memberikan nilai tambah bagi industri pertanian, termasuk pertanian nilam.
Tanpa bantuan dari universitas, potensi pertanian nilam di Aceh mungkin tidak tergali sepenuhnya, yang dapat mengakibatkan stagnasi dalam pengembangan sektor pertanian tersebut.
Salah satu fokus utama ARC adalah memastikan masyarakat petani dapat memperoleh harga jual yang lebih baik untuk produk nilam mereka. Dengan memperhitungkan potensi pendapatan dari setiap hektar tanaman nilam, ARC mengidentifikasi potensi besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh.
Syaifullah menekankan peran dosen (akademisi) dalam hal ini adalah untuk berkomitmen dalam membantu kemajuan masyarakat Aceh melalui pengembangan sektor pertanian, termasuk peningkatan hasil dan pendapatan bagi petani.
Model Pemberdayaan Nilam
Perwakilan Indika Nature mengajukan pertanyaan terkait model pemberdayaan nilam dengan masyarakat.
Syaifullah menjelaskan ada banyak cara, seperti funding dari pemerintah dan swasta. ARC mendapatkan pendanaan dari BRIN, BSI, Kedaireka dan lainnya untuk menjalankan operasionalnya.
Universitas telah mengambil peran penting dalam mendampingi berbagai aspek teknologi dan budidaya, serta mengawal proses pengembangan hingga tahap produksi.
Salah satu contoh nyata dari keterlibatan ini adalah kemitraan antara Universitas dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam program pembinaan desa di Lhong Raya, yang didukung pendanaan sebesar Rp5,3 miliar.
Program ini melibatkan rekrutmen 100 kelompok petani sebagai penerima manfaat utama. ARC dari universitas bertanggung jawab memberikan bimbingan teknis kepada para petani ini.
Selanjutnya, BSI turut serta memberikan dukungan berupa alokasi lahan seluas 5000 m2, pembangunan fasilitas termasuk tenda penyulingan, kebun percontohan, dan rumah pembelajaran, serta melibatkan PT U Green Aromatic Internasional dalam pembelian minyak nilam dari masyarakat.
Fasilitas lainnya seperti bibit tanaman dan kelengkapan lainnya tidak menimbulkan beban finansial bagi masyarakat karena didukung sepenuhnya oleh pendanaan BSI.
Di samping itu, terdapat model partisipasi masyarakat yang melibatkan pembagian hasil panen sebagai bentuk insentif tambahan. Pentingnya peran mitra lokal yang dapat dipercaya dalam mengawasi keseluruhan proses menjadi aspek yang ditekankan dalam konteks ini.
Peran universitas dalam mendampingi berbagai inisiatif dan proyek memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disebabkan oleh keberadaan keahlian dan sumber daya riset yang dimiliki universitas, yang memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam berbagai aspek, mulai dari pengembangan teknologi hingga praktik budidaya yang efektif.
Lebih jauh lagi, peran universitas juga terwujud dalam memastikan kelangsungan proses bisnis yang adil dan berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan keadilan.
Pandangan filosofis yang mendasari peran ini menekankan pentingnya orientasi pelayanan kepada kepentingan masyarakat secara luas, dan bukan semata-mata fokus pada aspek keuangan semata.
Konsep ini menegaskan keyakinan akan prinsip keadilan yang mendasari distribusi rezeki, kesejahteraan individu dan perusahaan dianggap sebagai hasil dari komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip sosial dan tanggung jawab korporat.
Kesimpulannya, peran universitas dalam mendampingi proyek-proyek ini tidak hanya memperkuat fondasi pengetahuan dan keahlian teknis, tetapi juga memberikan kontribusi yang substansial terhadap pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.[]
Dewi Suryani Sentosa, S.Sy., M.E. adalah anggota tim lembaga riset Atsiri Research Center-Universitas Syiah Kuala (ARC-USK) Banda Aceh.










Komentar